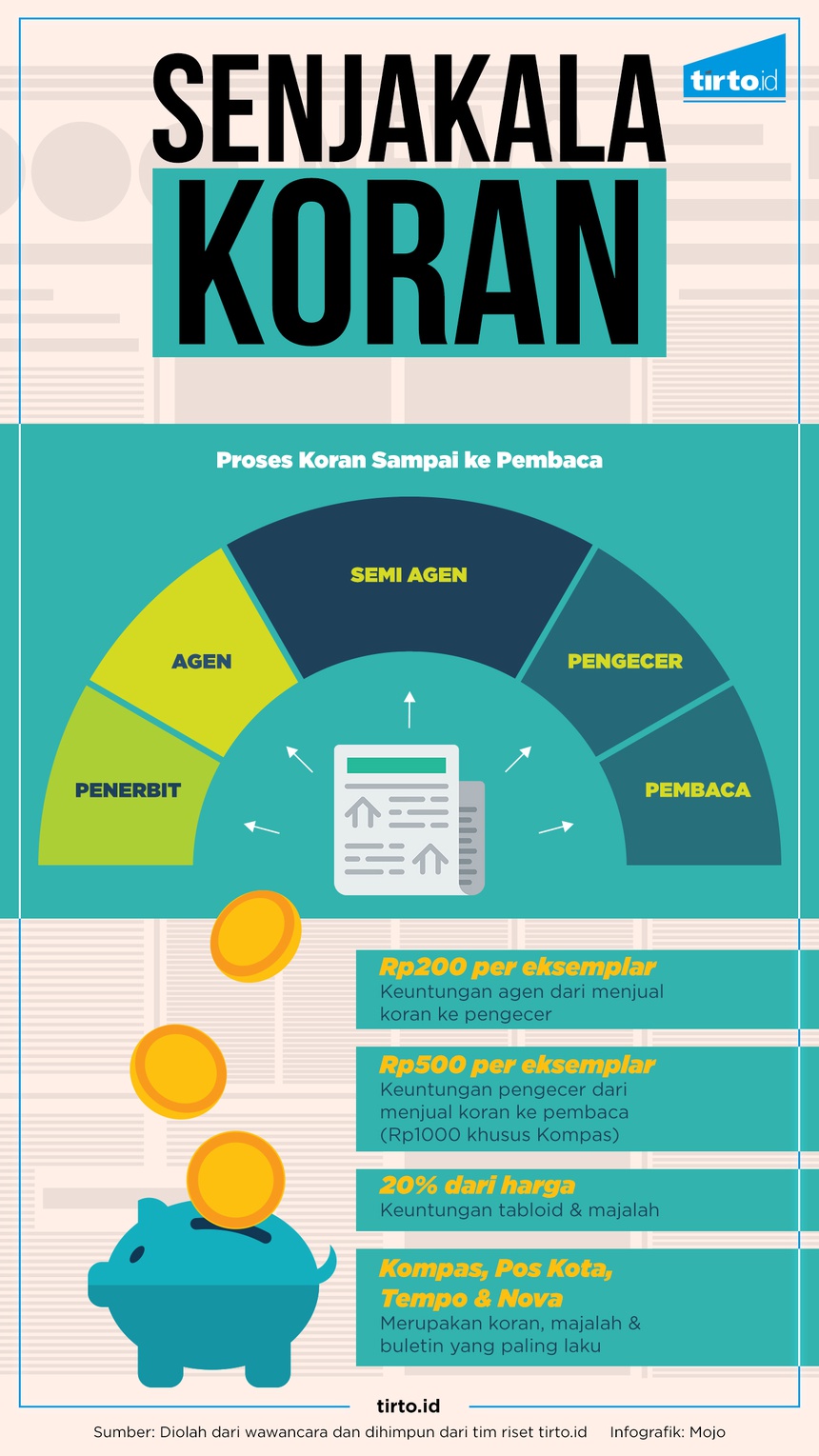Tanpa Soeharto, Freeport akan sulit beroperasi di Papua.
tirto.id - “Jauh sebelum kedatangan para penjelajah dari Eropa, penduduk asli Papua hanya mengambil serba sedikit dari alam,” tulis buku Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas (2008).
Bahkan ketika Kapten Johan Carstensz berlayar ke Papua pada 1623, orang Papua masih sedikit sekali mengambil dari alam Papua. Hanya babi, sagu dan umbi yang paling banyak diambil. Carstensz adalah orang Eropa pertama yang melihat salju di tengah daratan Papua. Apa yang dilihatnya itu dilaporkan dan jadi bahan tertawaan koleganya.
Pikir mereka, bagaimana mungkin ada salju di dekat Katulistiwa?
Ratusan tahun setelah Carstensz dianggap hanya mengigau, sebuah tim yang dipimpin orang Belanda bernama Hendrikus Albertus Lorentz pun mencoba mendaki pegunungan bersalju di tengan Papua itu.
Tim yang dipimpin Lorentz itu mengerahkan orang-orang Dayak Kenyah yang dijadikan juru angkut barang dalam ekspedisi tahun 1909. Orang-orang Dayak yang dari Kalimantan ini direkrut di Apo Kayan. Tak hanya dalam ekspedisi 1909, dalam ekspedisi orang-orang Belanda setelahnya, ekspedisi yang dipimpin Kapten Franssen Herderschee dari KNIL, orang-orang Dayak dikerahkan lagi. Tak hanya Dayak Kenyah, tapi juga Kayan. Orang-orang ini sangat kegirangan saat mereka melihat salju. Bahkan mereka kepingin membawanya pulang.
Namun bukan Carstensz atau Lorentz yang akan mengubah lanskap di Papua, melainkan Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel yang melakukan perjalanan pada 1936. Ekspedisi itu tak hanya mendaki puncak tertinggi di pegunungan tengah Papua yang dinamai Carstenz Pyramid. Yang paling penting adalah penemuan gunungan tembaga oleh Dozy, seorang ahli geologi. Penemuannya itu ditulisnya dalam sebuah laporan.
Bahkan ketika Kapten Johan Carstensz berlayar ke Papua pada 1623, orang Papua masih sedikit sekali mengambil dari alam Papua. Hanya babi, sagu dan umbi yang paling banyak diambil. Carstensz adalah orang Eropa pertama yang melihat salju di tengah daratan Papua. Apa yang dilihatnya itu dilaporkan dan jadi bahan tertawaan koleganya.
Pikir mereka, bagaimana mungkin ada salju di dekat Katulistiwa?
Ratusan tahun setelah Carstensz dianggap hanya mengigau, sebuah tim yang dipimpin orang Belanda bernama Hendrikus Albertus Lorentz pun mencoba mendaki pegunungan bersalju di tengan Papua itu.
Tim yang dipimpin Lorentz itu mengerahkan orang-orang Dayak Kenyah yang dijadikan juru angkut barang dalam ekspedisi tahun 1909. Orang-orang Dayak yang dari Kalimantan ini direkrut di Apo Kayan. Tak hanya dalam ekspedisi 1909, dalam ekspedisi orang-orang Belanda setelahnya, ekspedisi yang dipimpin Kapten Franssen Herderschee dari KNIL, orang-orang Dayak dikerahkan lagi. Tak hanya Dayak Kenyah, tapi juga Kayan. Orang-orang ini sangat kegirangan saat mereka melihat salju. Bahkan mereka kepingin membawanya pulang.
Namun bukan Carstensz atau Lorentz yang akan mengubah lanskap di Papua, melainkan Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel yang melakukan perjalanan pada 1936. Ekspedisi itu tak hanya mendaki puncak tertinggi di pegunungan tengah Papua yang dinamai Carstenz Pyramid. Yang paling penting adalah penemuan gunungan tembaga oleh Dozy, seorang ahli geologi. Penemuannya itu ditulisnya dalam sebuah laporan.
Temuan Forbes Wilson dan Jalan Buntu Sukarno
Apa yang ditemukan Dozy itu tak langsung dilirik banyak pihak. Apalagi tiga tahun setelah ekspedisi ini terjadi Perang Dunia II. Fokus banyak negara hanya tertuju pada perang. Barulah setelah Perang Dunia II selesai, apa yang ditemukan Dozy menarik minat sebuah perusahaan tambang dari Amerika bernama Freeport.Pada 1959, laporan Dozy itu sampai ke telinga Forbes Wilson, geolog Freeport. Wilson lantas menindaklanjutinya dengan berangkat ke Papua. Ia tiba pada 1960 dan terpukau oleh “gundukan harta karun” pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut itu. Dia begitu terpesona oleh hamparan bijih tembaga yang terhampar luas di permukaan tanah. Dalam laporan perjalanannya yang berjudul The Conquest of Cooper Mountain (1989), Wilson menyebut terdapat bijuh besi, tembaga, perak serta emas.
Ia membawa sejumlah batu dari Ertsberg pulang ke Amerika Serikat. Dari contoh-contoh yang dibawa Wilson, para analis Freeport menyatakan bahwa penambangan gunung itu bakal amat menguntungkan. Modal awal akan kembali hanya dalam tiga tahun, kata mereka.
Namun, Freeport menghadapi jalan buntu: Presiden Republik Indonesia, Sukarno, sedang pasang sikap keras terhadap kaum kapitalis Barat—menurutnya, merekalah agen-agen “penjajahan gaya baru.” Belum lagi soal perebutan wilayah di kepulauan Nusantara antara Indonesia dan Belanda. Saat itu, Sukarno getol menyerukan Trikora alias Tiga Komando Rakyat: 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, 2) Kibarkan Sang Merah-Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, dan 3) Bersiaplah dimobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Sampai akhirnya kekuatan politik Sukarno digembosi tentara nasional lewat peristiwa berdarah 1 Oktober 1965. Kekuasaan, secara berangsur tetapi seksama, pindah ke tangan Jenderal Soeharto, jenderal Angkatan Darat yang menorehkan tinta emas bagi sejarah Freeport di Papua. Freeport bersukacita dengan penguasa baru Indonesia yang pro modal asing ini.
Karpet Merah dari Soeharto
Soeharto mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 (UU No.1/1967) tentang Penanaman Modal. UU itu asing rupanya telah disahkan sejak 10 Januari 1967. Awal tahun 1967 tersebut Sukarno sebenarnya masih menjadi Presiden, namun kekuasaannya sudah tergerogoti sejak awal 1966. Sejak 25 Juli 1966 hingga 17 Oktober 1967, Soeharto adalah Ketua Presidium Kabinet yang menguasai pemerintahan menyusul keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966.Soeharto baru ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Nawaksara) ditolak MPRS. Langkah apa saja yang diambil Soeharto di awal statusnya sebagai pejabat presiden?
Salah satu yang berdampak panjang secara ekonomi adalah: memberikan kontrak karya kepada Freeport selama 30 tahun. Kontrak karya itu ditandatangani pada 7 April 1967, hanya sekitar tiga pekan setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden.
"Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi dan politik utama di Indonesia," tulis Denise Leith dalam Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia (2003).
Setelah Freeport, menurut Simon Felix Sembiring dalam Jalan Baru Untuk Tambang (2009), penikmat dari UU PMA tahun 1967 itu adalah Inco yang menambang nikel di Saroako, Sulawesi Selatan sejak 1968. Menurut Leith, pada 1970an, saat Freeport membangun infrastruktur pertambangannya, rezim Soeharto mengemis pembagian saham. Pejabat-pejabat Indonesia dikabarkan bolak-balik Jakarta-New York demi urusan itu.
Koran Indonesia Raya yang dipimpin sastrawan Mochtar Lubis merekam kejadian itu. “Beritanya kecil saja, tentang Menteri Pertambangan Prof. Soemantri Brodjonegoro yang berkunjung ke Amerika Serikat atas udangan maskapai Freeport Sulphur,” tulis Mochtar dalam Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di harian Indonesia Raya (1997). Ia mengatakan bahwa tindakan Soemantri itu (seorang pejabat negara, atas nama negara, memenuhi undangan perusahaan swasta asing) tidak patut.
Tetapi begitulah Orde Baru. Upaya untuk mendapatkan saham itu terus berlanjut. Pada 1973, Menteri Pertambangan pengganti Prof. Soemantri, Mohamad Sadli, diberi tugas “meninjau ulang” kontrak-kontrak antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan swasta, termasuk Freeport.
Dalam Pelaku Berkisah (peny. Thee Kian Wie, 2005), Sadli menyatakan bahwa pemerintah kadung terikat kontrak “generasi pertama” dengan Freeport. Menurut persyaratan kontrak itu, Freeport memperoleh masa bebas pajak selama tiga tahun, konsesi pajak (sebesar 35 persen untuk tujuh tahun berikutnya, dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain lima persen pajak penjualan.
“Segera sesudah kontrak ditandatangani, pemerintah menyadari bahwa kontrak itu perlu direvisi, agar memberikan hasil lebih banyak keuntungan ekonomi bagi Indonesia,” tulis Sadli.
Menurut Denise Leith, rezim Soeharto menginginkan saham sebesar 8,9 persen. Namun, Freeport tak langsung memenuhi permintaan Soeharto. Alasannya, perusahaan itu belum untung dan para pembeli mereka di Jepang meminta potongan harga bijih tembaga.
Tanggapan Soeharto bukan main: Ia ikut melindungi Freeport dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan minyak ke Jepang. Karena itulah, kata Leith, tercipta simbiosis mutualisme antara Freeport dan Indonesia. Dua tahun kemudian, Freeport memberikan jatah saham sebesar 8,5 persen dan royalti sebesar 1 persen kepada pemerintah Indonesia.
Merasa perlu menaruh wakilnya di Jakarta, kantor pusat Freeport di Amerika Serikat menunjuk Ali Budiardjo sebagai Kepala Perwakilan Freeport Indonesia. Ali adalah pemilik firma hukum Ali Budiardjo & Associates sekaligus kawan lama mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sebelumnya, sewaktu Forbes Wilson melobi Soeharto untuk menambang Ertsberg, Ali jadi penyambung lidahnya. Pada 1974, ia menggantikan Wilson sebagai Presiden Direktur Freeport.

Warisan Soeharto untuk Amerika
rafik
Hingga 1989, bijih-bijih tambang dari Ertsberg mengalir melalui pipa sepanjang 115 km ke Amamapare Freeport, tempat kapal-kapal pengakut menunggu. Menurut catatan International Bussines Promotion, gunung itu menghasilkan 32 juta ton bijih sebelum rata dengan tanah.Pada mulanya, Freeport hanya memiliki konsesi buat menambang wilayah seluas 10 ribu hektare. Namun, rezim Soeharto memberi izin perluasan hingga 2,5 juta hektare pada 1989, lewat kontrak anyar. Belakangan diketahui bahwa Freeport menemukan cadangan emas tak jauh dari Ertsberg. Tetapi kontrak Karya I yang seharusnya habis pada 1997 telanjur digantikan dengan Kontrak Karya II yang bakal jalan terus sampai 2021.
Kontrak karya inilah yang coba diubah oleh Jokowi tahun ini. Pemerintahan Jokowi ingin mengubah status dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tentu saja Freeport tidak tinggal diam. Mereka mengancam akan membawa Indonesia ke Arbitrase Internasional.
Itulah, Saudara, polemik warisan daripada Soeharto yang tak kunjung habis.
Namun, apakah ada soal yang lebih gawat ketimbang pemerintah yang kecele berkali-kali dalam kerja samanya dengan perusahaan asing? Tentu. Yang kerap hilang dalam pembicaraan tentang kontrak karya Freeport tidak lain dan tidak bukan ialah pemangku kepentingan terbesar di Papua: rakyat Papua itu sendiri.
Penyair Y. Thendra BP menuliskan situasi itu dalam sajaknya yang berjudul “Manusia Utama” (Manusia Utama, 2011):
nagawan into, kenapa kita orang terusir dari kita punya gunung salju abadi,
kita orang sebut itu nemangkawi (anak panah putih). kita orang amung mee,
manusia utama! kita punya emas dalam nemangkawi, tapi tidak disimpan
dalam honai. ke mana kita punya emas pergi?
sejak magaboarat negel jombei-peibei jadi ertsberg jadi grasberg,
suara kasuari hilang dari kita punya telinga. sejak kulit bia diganti rupiah,
kita orang terusir dari lembah tsinga, lembah Hoeya, dan lembah noema.
kenapa kita orang terusir dari nemangkawi?
nagawan into, bila masa pembebasan itu tiba:
sehelai daun lebar turun di sebelah barat
terbang kembali Laksana kuncup bunga ubi
tumbuh dan besar di tanah
muncul di kaki gunung...
https://tirto.id/freeport-di-papua-ialah-warisan-daripada-soeharto-cjrC