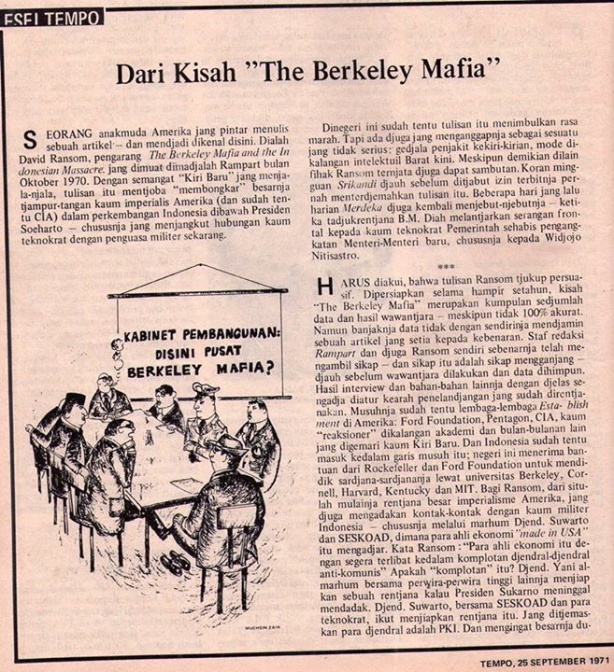Mari, untuk kali ini saja, kita mengambil gelagat naif. Dan dengan perangai lugu ini, kita anggap pertanyaan berikut bukanlah pertanyaan retoris:
Benarkah “Negara” yang sekarang identik dengan “Negara” yang berkuasa pada 1966, dan sebab itu menanggung dosa yang sama? Bisakah pendekatan legal semata-mata berlaku, yang melihat subyek, dalam hal ini “Negara”, sebagai identitas yang tak berubah?
Pertanyaan tersebut, tentu saja kita tahu, adalah pertanyaan retoris. Ia dicuatkan oleh Goenawan Mohamad yang secara sinis dan, sayangnya pula, wagu, mempertanyakan pentingnya wacana permintaan maaf terhadap korban kekerasan 1965 hari-hari ini. Untuk apa menghambur-hamburkan energi mendramatisasi penderitaan korban agar bisa mendapatkan perlakuan istimewa sekaligus menistakan pemerintahan yang sudah sama sekali berbeda? Bukankah kepala pemerintahan sekarang pada saat kejadian tragis tersebut berlangsung baru berusia lima tahun?
Tentu saja, GM, penulis yang santun dan subtil, tak mengartikulasikan pertanyaannya serupa parafrase blak-blakan barusan. Tetapi, saya cukup yakin, parafrase saya tak terlalu meleset dari apa yang dimaksudkannya melalui penyampaiannya yang samar. Dan karena GM nampaknya belum terlalu insaf dengan watak institusi bernama negara, perkenankan saya menjawab retorikanya yang seharusnya tidak meminta jawaban.
Perkenankan saya menjadi naif—menanggapi pertanyaan tak seriusnya dengan serius.
Dari mana kita mulai menanggapinya?
Pertama, dari celah pada pernyataan GM bahwa negara hari ini tak bisa disamakan dengan negara di masa silam yang, kendati kontroversial, disampaikannya tanpa argumentasi, dan hanyamenyebut-nyebut Marx tanpa berhasil meyakinkan saya apakah gagasan yang disampaikan GM yang memang dimaksud Marx.
Mari kita sambangi satu fakta. Faktanya, sejak waktu yang sudah sangat lama sejarah mengenal apa yang disebut dengan insan khayali. Perusahaan adalah insan khayali. Asosiasi adalah insan khayali. Serikat adalah insan khayali. Dan, tentu saja, negara adalah insan khayali. Rujukan saya mengatakan ini bukanlah diskursus-diskursus yang biasa ditepis enteng para penyalahpaham sebagai spekulasi tanpa dasar empiris. Rujukan saya adalah diskursus hukum—diskursus yang, mungkin perlu saya singgung sedikit, diterima sebagai penentu bagaimana setiap lelaku dalam kehidupan modern kita diatur.
Hukum lumrah membedakan dua subjek yang berbeda—insan alamiah dan insan yuridis. Insan alamiah adalah saya, Anda, serta setiap individu yang lahir, hidup, bernapas, makan, dan akan wafat sewajarnya manusia. Insan yuridis, sementara itu,mencakup wadah yang menaungi sekelompok orang—entah kita menyebutnya lembaga, institusi, organisasi. Entitas ini disebut insan bukannya tanpa alasan. Di mata hukum, pasalnya,memang, ia ditempatkanseakan-akan satu individu yang nyata. Ia dapat dituntut, dikenai sanksi, diadili, dan memang sejauh ini hanya dengan memperlakukannya demikian ia dapat menjadi subjek hukum—dapat diatur.
Karenanya, ia lazim juga menyandang sebutan persona ficta. Artinya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, insan khayali.
Kendati semua yang mempunyai nalar sehat bisa dipastikan sadar entitas ini diimajinasikan, tak ada yang mengatakan hukum positif cuma mengatur imajinasi kita manakala ia mengatur lembaga-lembaga. Kita, memang, tak akan bisa menemukan insan khayali secara harfiah berdenyut dan menapakkan kaki di atas wilayah hukum Indonesia. Paling nyata, apabila kita berpikir nyata berarti mempunyai jasad yang bisa disentuh, ia adalah bayangan yang diproyeksikan oleh jejaring yang mengonstitusi otak kita—sebuah delusi massal. Namun, tak ada yang pernah menyebutnya sebagai produk delusi massal.
Hukum tak pernah menganggap kristalisasi imajinasi kolektif ini sebagai sesuatu yang tak serius, bukan? Pemerintah kolonial tak pernah bermain-main pada saat berurusan dengan perhimpunan-perhimpunan yang menuntut kemerdekaan. Kita tak pernah membayangkan negara sebagai sekadar sekumpulan juru cap dokumen berkantor—kendati demikianlah realitas jasmaniah yang kita cerap sewaktu-waktu kita dijengkelkan dengan keruwetan-keruwetan tanpa juntrungan birokrasi.
Atau, mari kita sambangi pemikiran almarhum Benedict Anderson sejenak. Anggota satu bangsa paling kecil sekalipun, ia sempat menyampaikan, tak akan pernah menjumpai langsung satu persatu anggotanya. Bangsa ada, artinya, semata karena dibayangkan; semata karena saya membayangkan orang lain yang seharusnya asing dan sekadar kebetulan tinggal di gugus kepulauan yang sama dengan citra kemanusiaan yang sama dengan saya dan, sebaliknya, insan bersangkutan juga membayangkan hal yang sama.
Tetapi, anasir yang dibayangkan belaka ini membuktikan dirinya lebih berbahaya dari apa pun yang diciptakan manusia selepas revolusi industri. Insan khayali ini mungkin untuk mempunyai sentimen, pendirian, emosi—dan tentu saja kebencian. Satu bangsa dapat dikatakan membenci bangsa lain dan, persoalannya, betapapun sentimen ini sekadar diimajinasikan, ia tetap saja menggugah atau memaksa para anggotanya untuk secara nyata membenci anggota bangsa lain. Ketika jutaan insan tergugah atau setidaknya dituntut taat dengan sentimen kebencian sang insan khayali, tragedi paling mengerikan dapat menggedor pintu.
Tragedi 1965 adalah salah satunya.
Satu insan, pada saat itu, dapat membantai saudaranya sendiri dengan enteng. Satu keluarga harus merelakan sang ayah dibunuh di depan mereka agar mereka selamat. Warga desa yang memendam kebencian terhadap tetangganya bisa menghabisi tetangganya tanpa dihukum—cukup tunjuk sang tetangga komunis. Profesional yang tugasnya menemukan cara membunuh sebanyak sekaligus seefisien mungkin, seperti Anwar Kongo, bermunculan.
Tragedi merogohkan tangannya menggapai ceruk-ceruk terkecil kehidupan di Indonesia dan, pertanyaannya, karena apa? Banyak variabel ambil andil, memang. Tetapi, ia dipastikan tak akan pernah terjadi apabila negara tak pernah berhasil dikonstruksi sebagai insan khayali yang secara buta membenci kelompok komunis lantaran pengkhianatannya. Dan pada saat itu, kita tahu, semua harus mengindahkan amarah insan khayali ini, tak ada pilihan lain. Pilihan lainnya, kalau ia masih bisa disebut pilihan, adalah turut menjadi objek amarah negara—dianggap sebagai simpatisan komunis.
Saya, seperti GM, bisa mengatakan negara tidak stabil. Dan, bukankah saya sendiri terus-menerus mengatakan ia adalah sesuatu yang khayali—dikhayalkan? Tetapi, dari apa yang sudah kita lihat, saya jelas tak bisa sembarangan mengatakan yang khayali tersebut tidak berdampak nyata. Dan karena GM menggemari nukilan-nukilan cerdas, saya bisa menukil pernyataan Emile Durkheim dalam bukunya Elementary Forms of Religious Life untuk membantu meyakinkannya. “Terdapat satu ranah di mana rumus dari idealisme nyaris berlaku secara harfiah; ia adalah ranah yang sosial. Di sana, lebih dari di mana pun, gagasan menciptakan realitas.”
Namun, lebih jauh, insan khayali ini tak hanya melebur kesadaran sekerumun orang dan menjadikannya satu-kesatuan yang absurd sekaligus menakutkan. Ia merupakan jembatan penyambung sejarah dan mungkin merupakan teknologi yang paling efektif agar waktu tak tercerai berai menjadi repihanmomen yang berdiri sendiri-sendiri. Ambil ilustrasi yang diajukan David Graeber dalam bukunya Debt. Jikalau pada sebuah masyarakat suku seseorang wajarnya lunas utangnya saat insan yang memiutanginya meninggal, keberadaan insan khayali seperti negara menjadikan seorang pengutang apa pun yang terjadi terus tercatat hutangnya.
Seorang budak, setelah majikannya meninggal sekalipun, akan tetap menjadi budak di masyarakat. Anaknya, yang bahkan tak pernah mengetahui mengapa orang tuanya menjadi budak, akan menjadi budak. Warga satu negara, bahkan pada saat ia baru lahir, akan menanggung utang yang diambil negaranya pada periode kepemimpinan pejabat tertentu. Satu peristiwa di masa silam yang jauh sekalipun, artinya, akan terbawa dampaknya melintasi beberapa generasi. Semua bermula dari lembaga yang notabene tak stabil dan sekadar dibayangkan: negara.
Dan, bukankah demikian pula yang terjadi dengan kekerasan terhadap siapa-siapa yang didapuk bertautan dengan komunisme? Pejabat boleh berganti. Konstelasi politik lokal maupun global boleh mengalami perombakan. Akan tetapi, tak terlalu sulit untuk melihat bahwa sentimen ini masih terus direproduksi, dan pelbagai pihak bahkan menikmati pelanggengannya. Insan khayali negara Indonesia yang menguasai imajinasi kita, pasalnya, masihsama. Ia masihlah seseorang yang secara konyol membenci apa-apa yang berkenaan dengan komunisme—bahkan mereka yang kehidupan normalnya berakhir tanpa pernah tahu-menahu drama politik yang mendahului peristiwa 1965.
Kalaupun GM tak menyaksikan perlakuan yang diterima para penyintas tragedi 1965 untuk tahu imajinasi negara dapat menggugah kekerasan tak peduli siapa pejabatnya, ia seharusnya mendengar pernyataan-pernyataan Luhut belakangan—catatan pinggirnya sendiri toh merupakan tanggapan terhadap simposium yang menyediakan sesi untuk Bapak Kemenkopolhukam. Berita utama dari simposium tempo hari adalah Luhut menolak meminta maaf terhadap para korban 1965. Dan, yang paling menyakitkan, ia tak yakin bahwa benar-benar terjadi pembantaian massal di masa silam sebagaimana yang selama ini banyak diangkat.
Untuk apa di panggung simposium itu Luhutmembela mati-matian negara dari dusta yang dituduhkan kepadanya dengan argumen kopong? Untuk apa ia mempertaruhkan harga dirinya apabila negara memang sesuatu yang berubah sesegera pejabatnya berganti? Luhut, pasalnya, insaf. Negaranya adalah negara yang tak simpatik terhadap komunisme dan ia adalah pejabatnya, koordinator bidang politik hukum dan keamanannya, serta mantan petinggi militernya. Dalam konteks komunitas fiktifnya tersebut, Luhut tak sedang menjadi seseorang yang tak berperasaan dengan pernyataan-pernyataannya. Ia tengah menunaikan tugasnya dan, bukan tidak mungkin, berusaha menampilkan diri sebagai pahlawan untuk mereka.
Tetapi, GM tidak insaf.
Atau, kalau mau gunakan logika GM sendiri, mengapa presiden yang baru berusia lima tahun pada saat tragedi bergulir dan jelas tak terlibat apa pun, masih ragu meminta maaf kepada para korban? Kalau permintaan maaf adalah tindakan yang benar dan Joko Widodo tak mempunyai beban apa pun untuk melakukannya, mengapa ia tidak melakoninya sesegera mungkin?
Saya kira, mengatakan negara sudah berubah tidaklah semudah itu. Insan khayali negara Indonesia saat ini masihlah insan yang sama pembencinya dengan dirinya lima puluh tahun silam. Dan kepentingan para pejabat, agar dianggap pejabat yang sahih, serta pusparagam pihak yang membutuhkan musuh-musuh imajiner untuk membumbui kehidupan mereka dengan drama adalah berlakon tetap sesuai naskahagar citra insan khayali ini terus lestari—tak peduli ia mengorbankan rasa keadilan, empati terhadap penderitaan, atau bahkan sekadar akal sehat. Tak peduli ia mengekalkan kekerasan-kekerasan yang kini sudah tak beralasan dan hanya dapat dikatakan keji.
Dan inilah mengapa permintaan maaf menjadi sesuatu yang berarti sekaligus mungkin menjadi tindakan yang radikal. Dengan permintaan maaf, sosok yang ditabalkan selaku pemimpin negara ini mempunyai peluang menggeser citra insan khayali Indonesia yang pembenci ini menjadi seseorang yang lebih masuk akal. Dan, bersamanya, mematahkan norma kekerasan yang menjadi habitus pada saat bertatapan dengan mereka yang didefinisikan sebagai liyan sepanjang sejarah Indonesia yang kita ketahui.
Saya tak tahu apa arti permintaan maaf bagi GM sampai-sampai ia diartikan sesuatu yang merendahkan derajat kepala negara. Tetapi, kalaupun ia harus merendahkan simbol negara, penistaan diri simbolis inilah yang diperlukan untuk mengirimkan pesan kekerasan bukanlah sesuatu yang mempunyai tempat di tanah air ini. Kekerasan bukanlah cara untuk menjadi Indonesia.
Ia belum tentu berhasil memang. Kemungkinannya tidak berhasil dan mencederai kepopuleran kepala negara malah lebih besar. Namun, ia adalah hal paling berperasaan yang mungkin diambil di antara pilihan-pilihan lainnya.