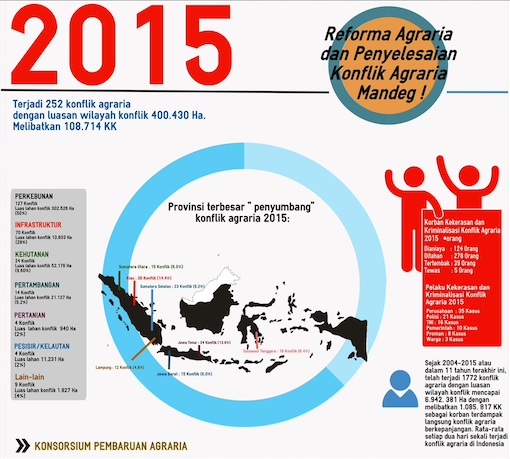by
Yusni Aziz
on
February 26, 2016
Sore itu, di sebuah kafe di kawasan Kemang, ia tidak datang
sendirian. Di belakangnya saya lihat dua orang mengikutinya secara
perlahan, mengimbangi derap langkahnya yang penuh kehati-hatian. Saya
spontan berdiri setelah melihatnya, dan tersenyum lebar. “Halo pak
Yoyok”, sambut saya yang dibalas hangat jabat tangannya. Ia kemudian
memperkenalkan saya ke kedua rekannya. Dinar, seorang ahli biologi yang
saat itu tengah hamil besar, dan Sanca, suaminya, seorang peneliti yang
juga aktivis seni rupa.
Mereka bertiga adalah sebagian dari pengurus Sekolah Ekonomika Demokratika (SED), atau juga disebut
School of Democratic Economics (SDE). Sekolah yang kiprahnya membuat tim RUANG penasaran, dan kami rasa sangat patut untuk diketahui oleh para sahabat.
Hendro Sangkoyo, atau biasa dipanggil Yoyok, merupakan salah satu
pendiri sekolah tersebut. Setelah lulus dari jurusan Arsitektur ITB, ia
melanjutkan studi tentang Perencanaan Wilayah dan Kota dan Kajian Asia
Tenggara, dan kemudian menyambungnya dengan
Planning Theory and Comparative Politics di
Universitas Cornell, Amerika Serikat. Sebelum pendirian SED di tahun
2007, ia sempat mengajar di Institut Teknologi Indonesia, menjadi
peneliti dan pengajar tamu di Royal Melbourne Institute of Technology,
Universitas Melbourne, dan Cornell. Setelah semuanya telah memesan
makanan dan minum, pembicaraan pun kami mulai.
Yusni Aziz (YA): Sebelum pertemuan ini, kami sudah berusaha
mencari informasi tentang SED di internet. Namun sangat minim sekali
data yang kami dapatkan. Apa pak Yoyok bisa menceritakan lebih jauh
mengenai sekolah ini?
Hendro Sangkoyo (HS): Ide awalnya muncul sekitar 20
tahun yang lalu, dari rangkaian perjalanan pribadi untuk belajar
memahami krisis di kepulauan Indonesia. Ceritanya di mana-mana seperti
ini. Di Kalimantan Barat, seorang tetua yang bertahun-tahun merintis
gerakan akar-rumput di situ mengajak ikut keluyuran belajar. Suatu
ketika saya berdiskusi mendalam dengan sekitar seratus anak muda Dayak,
mendengarkan tuturan mereka tentang perubahan di kampung halaman mereka;
kapan terakhir kali mereka masuk sungai; kenapa tidak ke sana lagi, dan
sebagainya. Ternyata, sungai-sungai yang melekat dengan sejarah sosial
dan pembentukan permukiman mereka pelan-pelan terpenggal oleh kegiatan
pembalakan, ditimbun untuk jalan-kayu gelondongan, banyak anak sungai
akhirnya mati tersumbat
. Ruang hidup di pedalaman pulau raksasa itu memang sejak 1970-an diperlakukan sebagai lansekap operasional /
operational landscape[1]
dari proses perluasan industri dan wilayah perkotaan – suatu aksi
membongkar dan mengeruk hasil alam yang seringkali kita tak acuhkan
.
Pada tahun 2007, menjelang pembukaan SDE, kawan-kawan yang ikut
merintis awal pendiriannya mempertimbangkan berbagai bentuk organisasi
dominan sampai akhir abad kedua puluh, seringkali di bawah rubrik
“masyarakat sipil”, tidak jarang yang cukup miskin imajinasi sosialnya.
Karena moda energetikanya, acapkali gerakan warga terpelajar ini lebih
repot dengan urusan manajerial dalam diri dan jaringannya, atau menjadi
birokratis seperti komponen-komponen hirarkis dari alur perakitan di
pabrik, seperti
taylorism.[2]
Untuk menghindari salah paham, perlu dikatakan bahwa menghimpun
kesepakatan untuk bertindak menjawab krisis secara kompak
(“pengorganisasian”) itu tak tergantikan pentingnya. Tak kalah
pentingnya adalah bagaimana membuka ruang-tutur tandingan buat orang
biasa untuk mengemukakan dan mempertukarkan pengetahuan akan lintasan
perubahan yang dialaminya. Dalam hal ruang bertutur tandingan tersebut,
imajinasi
rhizomatic learning dari Deleuze dan Guattari atau berbagai pengalaman menyejarah di negara dunia ketiga juga tidak bisa diabaikan
. Rizoma
artinya perambatan horizontal dari organisme bawah tanah, seperti akar
pohon beringin atau sulur-suluran. Dari permukaan nampak tunggal, tetapi
di bawahnya jauh lebih rumit. Proses belajar dengan pemahaman macam ini
penting, karena membuka ruang bagi semua orang untuk dapat membalik
krisis dengan model belajar yang non-hirarkis dan tidak menunggu
siapa-siapa. Sebaliknya, kapan sebuah tindakan kolektif harus dilakukan
belum tentu perlu mengacu pada tuntutan kemendesakan atau jadwal-jadwal
acara dari “organisasi pendamping”, patronnya, atau kantor-kantor
pengurus publik.
SDE mengajak menyuburkan ruang bertutur tandingan yang berdimensi
kemanusiaan dan ekologis, arena bagi warga biasa untuk mengemukakan
cerita-cerita perubahan yang selama ini didominasi oleh representasi
sempit bahkan distortif oleh jejaring pembentukan pengetahuan yang
mengasingkan pengalaman kolektif. Kata kunci utamanya adalah krisis.
Ruang ini akan menjadi arena perlawanan terhadap proses yang membuat
krisis ini semakin dalam dan belum pernah mengalami pembalikan. Demikian
pula, arena tersebut memungkinkan banyak orang berperan dalam tindakan
menyembuhkan/memulihkan kerusakan yang terus meluas.
YA: Krisis seperti apa yang dimaksud bapak ?
HS: Sebuah krisis berskala global yang sejarahnya
bisa ditarik jauh ke masa revolusi industri, saat terjadi peningkatan
kebutuhan akan bahan mentah. Di masa awal itu Karl Marx misalnya telah
mengenali ada gap yang membesar antara dua jenis metabolisme. Pertama,
metabolisme untuk kepentingan reproduksi yang instruksinya genetik.
Misalnya, kalau kamu makan 10 hari sekali juga tidak akan makin sehat
dan sejahtera. Kebutuhanmu
kan tetap.
Nah, yang kedua
ini biang keroknya – teknometabolisme. Dia melayani bukan cuma
reproduksi, juga akumulasi dari sistem pendukung kehidupan
rakitan/jadi-jadian. Misalnya, kebutuhan akan kota yang lebih
fancy meskipun tidak pernah mengatasi masalahnya sendiri—jalan
macet memunculkan layanan helikopter bagi yang mampu. Kebutuhan rakitan
yang dipicu oleh sektor pasokan tersebut tidak ada batasnya,
ad infinitum.

Pertumbuhan kota tanpa batas menjadi sumber meningkatnya krisis sosial ekologis.
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/08/Fairmont%2c-Raffles%2c-dan-Target-Wisman-di-Indonesia
Metabolisme yang pertama bersifat tetap, namun teknometabolisme
memperbesar gap di antara metabolisme masyarakat manusia dengan
metabolisme reproduksi sistem kehidupan di biosfera. Pembesaran gap itu
disebut sebagai
metabolic rift, sobekan metabolis, atau
ecological rift.
SED mengajukan penglihatan bahwa harus ada imperatif untuk membalik
logika pemburukan krisis ini. Kami ajukan agenda belajar tandingan yang
ujung tombaknya bersisi tiga. Pertama, harus ada rasionalitas tandingan
dari konsumsi ruang, bahan dan energi—termasuk penggunaan tenaga dan
waktu kerja orang untuk melayani reproduksinya sendiri. Misalnya,
sekarang anak-anak di kampung yang tidak punya pekerjaan layak bersedia
menyabung nyawa dengan waktu kerja lebih dari 12 jam sebagai TKI atau
TKW di pinggiran kota bahkan di seberang lautan. Berapa juta hektar
wilayah daratan pulau yang dikuasai untuk industri ekstraktif? Harus ada
rasionalitas tandingan. Apa tandingannya?
Harus ada respons sosial besar-besaran dan sistematis untuk menolak
perusakan syarat-syarat keselamatan manusia dan keutuhan biosfera, serta
pemulihan ruang-ruang hidup. Ini bukan gagasan abstrak, melainkan
sesuatu yang bisa dikerjakan siapa saja di ruang-ruang hidupnya
sendiri—yang secara generik kami kodifikasi sebagai
historical social-ecological entity, atau kesatuan sosial ekologis menyejarah.
Jadi, kami melihat kampung bukan sebagai penanda tempat, seperti apa
yang terjadi pada Kampung Ambon atau Kampung Kebun Kacang di Jakarta
sekarang, misalnya. Tetapi kampung dengan subyek sejarah di situ,
beserta sejarah sosial ekologisnya. Kenapa suatu kampung berada di
lembah, karena kedekatannya dengan aliran air. Jika kita paham konteks
reproduksi sosial dari sebuah kesatuan semacam itu, kita bisa mengerti
sistem pendukung kehidupan yang harus mati-matian dipertahankan di situ.
Kedua, apa protokol atau
framework dari rasionalitas tandingan ini.
Mengurus gitu ya, tapi
kepengurusan yang
seperti apa? Saya lihat pengurus publik saat ini begitu sempitnya
melihat apa yang harus dikembangkan dan apa yang justru harus dijaga
supaya tidak berubah; sistem kenegaraan untuk memelihara aset bersama
terpenting yaitu ruang-ruang hidup bersama dan keselamatan warga-negara,
justru sulit sekali dicari dalam kenyataan. Misalnya, apa masih bisa
kita biarkan jika menteri atau presiden masih terus berbicara tentang
menaikkan pertumbuhan, apalagi sudah masuk dalam klub G20, tanpa
pertimbangan sama-sekali mengenai hal-hal tadi? Tunggu dulu…
sektor-sektor yang difasilitasi habis-habisan di garis depan pertumbuhan
itu, seperti
logging, perkebunan sawit, pertambangan ekspor
berskala raksasa, jelas merusak jaminan jangka panjang kehidupan di
kepulauan Indonesia. Ada tidak yang merespons dengan kritis rencana
menaikkan pendapatan domestik brutto yang gegabah seperti itu?
Rasionalitasnya harus dikoreksi dulu, baru protokolnya.
Ujung tombak ketiga ini paling sulit, cara belajarnya. Anda arsitek,
lalu saya, misalnya, insinyur teknik sipil, dia ahli ekologis, dan kita
bersama melihat persoalan yang lebih besar. Belajarnya seperti apa?
Bagaimana mengajak lawan-belajar,
para manajer negara yang sekarang sedang dipimpin oleh Jokowi ini, untuk mulai mendengar?
Lantas agenda belajarnya apa? Apa yang kita musti pelajari? Sebagai
ilustrasi, di tahun 2015 ini kami bersama berbagai regu-regu belajar
lainnya menginjak tahun kedua belajar bersama dengan jejaring komunitas
dengan ±50.000 warga, di lereng utara Gunung Halimun. Proses perubahan
sosial-ekologis selama dua puluh lima tahun terakhir, yang dipicu oleh
pembongkaran bentang alam untuk pertambangan, telah menjadi sebuah
krisis yang terus memburuk, dan dampak dari cerita pembongkaran di
lereng itu meluas sampai dengan kehidupan terumbu karang dan biota laut
di kepulauan Seribu. Agenda belajarnya tidak mungkin ditemukan lewat
pengkajian, perencanaan atau perumusan anggaran di kota. Dalam tempo
kurang dari satu generasi kehidupan warga berubah dramatis. Sebutir
tomat harus dibeli seharga 500 rupiah. Penghargaan pada tani-pangan dan
tani pekarangan hampir hilang. Siklus kehidupan lereng gunung
dihancurkan. Kesadaran akan dimensi melingkar/siklis dari waktu
menghilang, juga pada warga usia muda.

Tambang Emas Pongkor di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, Jawa Barat
Sumber: http://warmada.staff.ugm.ac.id/Photos/tambang/images/pongkor1.jpg
Dalam cerita seperti itu, proses belajarnya tidak bisa cepat seperti
“ayo sekarang kita berubah!” Kehadiran para pelajar-tamu seperti kami
hanyalah sebagai semacam tali penghubung untuk menciptakan ruang
bertutur bagi banyak orang biasa, tentang bagaimana perubahan menurut
pengalaman batin warga sendiri. Soalnya bukan pengelolaan pengetahuan
, tapi pengelolaan proses belajar
. Bagaimana
melancarkan proses belajar yang rumit, yang melibatkan warga kampung
dengan berbagai kecakapan dan keterbatasannya, arsitek, ahli ekonomi,
etnografer, dokter, akhli kesehatan masyarakat, akhli geologi
tata-lingkungan dan sebagainya—yang juga serba terbatas
pengetahuannya—untuk memahami dan mencoba mengatasi krisis ini
bersama-sama.
Memahami imajinasi konstruksi politik, atau
political construct, yang membuat kita “jauh dari tanah”, juga penting. Misalnya, untuk
ngomongin terobosan
dalam pemerintah, maka makna dari institusinya itu harus kita lucuti
dari konotasi kolonialnya. Kami tidak pernah memakai kata “pemerintah”,
kami selalu memakai istilah “pengurus publik” untuk institusi publik.
PEMDA gimana? Ya, pengurus daerah. Karena akar kata “pemerintah” itu
dalam penggunaan sehari-hari adalah“perintah.” Artinya, di dalam
sikap mental kita,
kita/warga harus patuh pada sang perintah itu. Kalau kita gunakan
kata-kunci “urus”/kepengurusan, para pegawai di berbagai kantor pengurus
publik kita tempatkan pada peran utamanya, yaitu pelayan, atau jongos.
Sekarang siapa kepala jongosnya? Ya, Jokowi namanya. Jadi dengan
sendirinya ada satu proses demokratisasi di dalam pikiran.
Nah sekarang,
siapa yang sesungguhnya mengendalikan perubahan? Pengurus publik? Perluasan
kapital industrial sekarang berlangsung di bawah koordinasi dan
bayang-bayang dari kapital keuangan/perbankan yang mengalami kemajuan
pesat dalam proses akumulasi, terutama sejak 1980an. Hal ini juga perlu
dimengerti oleh dunia pendidikan dan profesi arsitektur. Akumulasi
berlebihan pada saat ini dipicu oleh kapital keuangan, yang lebih
memudahkan pencaplokan ruang dan valuasi ekonomik atas infrastruktur
sosial-ekologis, seperti pegunungan dan wilayah resapan air di pulau
Jawa dan pulau-pulau lainnya. Tapi, kita tidak pernah mempelajarinya
selain sebagai peluang bagi profesi, bukan pertimbangan kunci untuk
menetapkan persyaratan bagi penciptaan dan perluasan ruang-ruang
perkotaan.
Henri Lefebvre juga mengajukan bahwa sekarang kita sebetulnya sudah
memasuki era “urbanisasi berskala planeter.” Salah satu pelajar gejala
ini, Neil Brenner dari laboratorium perkotaan universitas Harvard,
misalnya, mendorong lebih jauh pengamatan Lefebvre, bahwa untuk
mempertahankan keberlanjutan proses urbanisasi/industrialisasi tersebut,
wilayah-wilayah “bukan urban” berperan vital sebagai “lansekap
operasional”. Warga di banyak lansekap operasional
urbanisasi/industrialisasi paham mengenai gejala ini, bahkan menjadi
korbannya. Wilayah-wilayah pedalaman Kalimantan dibongkar untuk memasok
batubara bagi pembangkitan energi dan industri di Jakarta. Sumber-sumber
energi primer dari daratan dan perairan kepulauan dikeruk dan diekspor
untuk mendukung kehidupan kota/industri di Jepang atau di Guangzhou.
YA: Jadi hanya ada sebagian yang menjadi kota dan sebagian lainnya operational landscape?
HS: “Urbanisasi planeter” dalam fikiran Lefebvre
melahirkan bagi-kerja spasial di antara lansekap-operasional dan situs
proses urbanisasi/industrialisasi. Kota selalu membesarkan
selubung-selubung dari sistem pendukungnya, dalam sebuah proses tak
kunjung usai yang disebut sebagai “perusakan kreatif.” Kampung-kampung
kota dengan sejarah sosial panjang dalam satu generasi sejak 1980an
telah berubah menjadi “segitiga emas” bagi industri properti, dengan
kerumunan
superblok untuk penghuni barunya. Jadi kota sendiri
telah menjadi sebuah lansekap operasional di mana manusia boleh
dipindah-pindahkan atau dikorbankan
, karena ada kebutuhan
perusakan-kreatif tanpa-batas itu tadi. Ini semua bonanza untuk dunia
penciptaan arsitektur. Meskipun misalnya hal ini terjadi di masa lalu
tanpa campur-tangan generasi baru arsitek yang baru muncul, tetapi
seharusnya kita ikut bertanggung jawab atau ikut pening untuk mencegah
proses serupa berjalan tanpa kendali.
Nah sekarang, bagaimana kita membayangkan arsitektur dan urbanisme
yang mengandung unsur terobosan untuk mengatasi krisis, dan mampu
menyuburkan daya cipta
gila-gilaan dari anak muda yang sedang belajar arsitektur itu?
YA: Lantas apakah bapak pernah terlibat dalam penggodokan kurikulum studi arsitektur dan apa ada yang harus diubah?
HS: Bukan hanya menghimbau, tetapi sejak dulu
mencoba mengintervensi langsung, meski bisa dibilang gagal. Saya
mengemukakan tantangan, apakah kearifan dan pengetahuan pokok yang harus
disiapkan untuk menghadapi krisis yang membesar dengan cepat ini?
Bagaimana pembentukan pengetahuannya? Mungkin mahasiswa semester pertama
tidak perlu mengkaji banyak teori. Lihat dulu kenyataan, lalu
berpikir sendiri, apa yang sebenarnya berlangsung dulu dan sekarang, bagaimana duduk-perkaranya, dan apa yang harus dilakukan?
Setiap daerah di kepulauan kita mencatat lintasan pembangkitan dan
pemburukan krisisnya sendiri-sendiri, menurut kekhasan sejarah
sosial-ekologis di situ. Oleh karenanya terobosan atau pemecahan masalah
yang muncul dari profesi-profesi keteknikan juga harus “membumi”,
bertumpu pada pemahaman yang baik atas lintasan perubahan di situ. Kalau
sekarang ini, kita seperti cowok atau cewek panggilan saja.
Persis seperti itu. Karena
kita tidak mau membicarakan apalagi menjawab masalah krisis yang besar
atau genting, kita mirip dengan seseorang yang hanya mencari kesenangan
dari daya cipta kita… aku, aku, aku.
Misalnya, keterkaitan arsitektur dengan pengurusan perubahan. Apakah aturan yang memperbolehkan pencaplokan lahan/
land grab
besar-besaran menjadi gosip politik sehari-hari di antara kita? Menurut
berbagai data resmi, sekitar 5,1 juta hektar lahan sawit di Indonesia
itu dikuasai oleh 29 orang saja
lho! Dari sebuah riset kecil,
kami menemukan bahwa ada lima instrumen hukum/perundang-undangan yang
secara tidak langsung memperbolehkan monopoli penggunaan dan pencaplokan
ruang-ruang daratan hingga 100 tahun lamanya. Saya tidak heran melihat
pendidikan kita miskin sekali. Seluruh imajinasi kita tentang
pembentukan pengetahuan, konteks zaman, basis krisis, daya dobrak itu
miskin. Belum lagi membicarakan cara belajar yang dikelola oleh
kanal-kanal pendidikan resmi.

Pencakupan hutan untuk lahan kelapa sawit di Kalimantan. ©Rhett A. Butler
YA: Saya ingin mengaitkan dengan metode penataan kota. Pak
Yoyok pernah mengatakan, dalam sebuah wawancara, bahwa modernisme perlu
dikritisi lebih lanjut. Lantas apakah sudah terpikirkan alternatif
tandingan terhadap modernisme yang dipakai pemerintah kita dalam
mengembangkan kota Indonesia?
HS: Saya tidak yakin sebetulnya bahwa beberapa
generasi pengurus publik kita selama ini secara kolektif mengerti dan
secara sadar memilih ideologi modernisasi. Daya pukau modernisasi itu
sendiri sudah lama rontok di negeri-negeri industri maju. Eropa, ujung
depan dari modernisasi sendiri, sekarang harus memeriksa jati-diri
kolektifnya dan pencapaian pencerahan dari masa lampaunya. Ketika
proporsi warga dari negara bekas jajahan di ruang-ruang hidupnya di
Afrika, Amerika Tengah dan Amerika Latin yang menetap atau mencoba
peruntungan di negara-negara maju membesar, rasisme tumbuh sebagai
persoalan kelas.
Ilustrasi lain tentang ilusi modernisasi adalah keyakinan dan petuah
bahwa “negara-negara sedang berkembang” seperti Indonesia akan mampu
untuk menempuh lintasan modernisasi ekologis/
ecological modernization.
Memang sekarang kita harus main bongkar, memacu industri keruk. Tapi
ketika nilai uang dari produksi dan konsumsi telah mencapai tingkat yang
memadai, kita akan menjadi jauh lebih pembersih dan ramah pada alam dan
manusia. Salah satu penjelasan formal dari kepercayaan tersebut adalah
kurva-lingkungan hidup dari Kuznets, yang menunjukkan korelasi di antara
pendapatan dengan moda transaksi dengan alam.
[3]
Dulu Jerman dan Inggris berkembang lewat industrialisasi yang jorok
sekali. Tetapi, ketika GDP-nya sudah menembus angka tertentu, sistem
produksi barang di situ menjadi “bersih.” Apa yang tidak dituturkan di
sini adalah bahwa dalam rerantai-pasokan barang industrial,
komponen-komponen industri yang paling buruk, mencemari, atau paling
rendah nilai-tukar yang diciptakannya pindah lokasi ke negara-negara
yang jauh lebih lunak regulasi lingkungan hidupnya.
Lalu tepat sepuluh tahun lalu, Mathias Wackernagel dan William Rees mengembangkan kerangka tuturan telapak-ekologis/
ecological footprint.[4]
Telapak ekologis Tokyo di tahun 2009 sudah lima kali lipat luas seluruh
kepulauan Jepang. Ke mana dia dibebankan atau dipindahkan? Antara lain
juga ke kita di sini. Pasar industri otomotifnya, ekstraksi logam
dasarnya, .
Ironi dalam tuturan modernitas, misalnya, bisa dipelajari dari salah
satu pulau terkering di Indonesia timur, yaitu pulau Adonara. Begitu
kecilnya lubang lesung yang mereka pakai menumbuk menunjukkan sangat
terbatasnya produksi bulir-buliran di situ. Kalau di sekitar April hujan
turun, mereka bisa menyimpan jagung. Jika tidak ada hujan, mereka
kemungkinan harus membeli sumber zat tepung untuk setahun. Ketika mereka
melakukan proses reproduksi di tingkat keluarga, mereka dilatih untuk
bersabar, seperti melakukan hibernasi. Tingkat konsumsinya pelan, dan
anak-anak dilatih untuk puas dalam berkonsumsi serba terbatas. Sejarah
ruang waktu dari sejarah ekologis dan sosial di situ tidak mungkin kita
plot pada angan-angan tentang trajektori perubahan menjadi “yang
modern.” Kontras sekali dengan citra modernitas di kota-kota besar yang
konsumsinya dan penggunaan energinya besar sekali. Kalau warga kepulauan
diminta untuk berbagi impian tentang konsumsi ruang, waktu, bahan dan
energi seperti di simpul-simpul perkotaan kita, artinya sistem
pengurusan publik kita bisa dikatakan buta krisis. Kita bahkan tidak
perduli untuk menghancurkan rumah kita sendiri, dengan mempercepat
transformasi dalam konsumsi sosial, seperti aksi bunuh diri
besar-besaran.
Kembali ke pendidikan, apakah mereka mau kembali berada di tengah atau sedang minggir teratur,
decentering? Melakukan divestasi dan melayani pasar saja?
YA: Jadi, SED juga mempelajari sistem hidup beberapa
kepulauan Indonesia untuk diolah lebih lanjut guna mencari tandingan
terhadap krisis?
HS: Ada satu interaksi yang terus menerus dan tidak
ada habisnya untuk ikut dalam proses pembentukan pengetahuan tandingan
dan bertindak,
bolak-balik. Ada tiga sektor belajar. Pertama,
Regu Belajar orang biasa. Bisa sebuah kampung/KSEM, atau beberapa guru-besar, atau jejaring aktivis akar-rumput, misalnya.
Sektor belajar kedua mencakup berbagai
regu,
badan pendidikan atau riset.
Yang paling susah berubah adalah mereka yang mendapat manfaat terbesar
dari status quo ini. Misalnya, semua disiplin yang menyangkut penataan
keuangan dan ruang binaan.
Profesi arsitektur sudah barang tentu secara umum masuk dalam golongan ini secara umum, karena dia terkait erat dengan proses pembesaran
lansekap operasional itu tadi.
Yang ketiga adalah
gugus belajar pengurus publik, misalnya
pengurus lokal seperti kepala desa atau pemimpin komunitas. Kami bisa
bergerak dengan siapa saja, tanpa mau sok jago. Pengetahuan itu
seharusnya tidak seperti imajinasi korporasi yang bisa dikuasai, bahkan
harus dilengkapi dengan
copyright.
YA: Lantas pemilihan lokasi belajarnya berdasarkan apa?
HS: Dengan berbagai keterbatasan dan beberapa
pertimbangan lain, siasat belajar yang kami pilih tidak sepenuhnya
berbeda topologinya dari imajinasi
moda belajar rhizomatik yang disinggung tadi
. Lansekap belajar utama kami
adalah Asia Timur, terutama kepulauan Indonesia. Lokasi belajar bukan
hasil pilihan acak, karena permintaan selalu muncul dari garis depan
krisis.
Selain riset mandiri kami sendiri, kegiatan kolaboratif kami umumnya
berdasarkan undangan belajar bersama. Kami juga belajar bersama dan dari
mitra belajar di tempat-tempat lain di Asia daratan, Sebaliknya,
berbagi catatan tentang bagaimana menghadapi dinamika krisis di
Indonesia juga menjadi penting untuk kawan-kawan di wilayah Bumi
lainnya.
Nah, baru-baru ini kami juga sedang belajar bersama teman-teman Maluku. Mungkin Sanca bisa menceritakannya.
Sanca (SP): Bulan Februari kemarin kami diajak
teman-teman untuk melihat persoalan di Maluku. Lokasi belajarnya di
kampung orang gunung yang sederhana sekali gaya-hidupnya. Mereka hidup
tanpa memakai baju, berbalut kain kepala merah. Mereka biasanya berburu
dan meramu tanaman. Persoalan pertama yaitu pola hidup berburu dan
meramu mereka terbatasi dengan hadirnya taman nasional. Mereka selalu
dituduh sebagai perusak. Padahal mereka sudah di sana terlebih dahulu.
Kami melanjutkan ke pulau Buru, tempat tahanan politik dahulu. Di
zaman Soekarno, pulau Buru sudah dilihat sebagai pulau yang cocok untuk
transmigrasi karena penduduknya masih sedikit dan dataran rendahnya baik
untuk pertanian. Namun ide itu tidak jadi dilaksanakan, karena yang
dikirim malah para tapol. Setelah itu baru masuk transmigran dari Jawa
dan Madura yang menggarap sawahnya sendiri. Saat ini, persoalannya
datang dari tambang emas. Aneh, tetapi tambang emas yang kita temukan
selalu di tempat-tempat sumber kehidupan seperti sawah, atau di hulu,
sumber air. Tambang emasnya
gila-gilaan, hingga mengundang kedatangan puluhan ribu penambang luar.
Persoalan lain muncul dari penggunaan merkuri yang berdampak pada
pencemaran padi dan ikan-ikan. Kasus bayi cacat juga sudah ada.

Perkampungan ilegal penambang emas di Pulau Buru. Sumber: http://beritaenam.com/view.php?id=20151127045736
YA: Jadi, sebelumnya dilakukan pemetaan terhadap krisis yang
terjadi, kemudian belajar bersama masyarakat untuk mencoba menandingi
itu?
SP: Iya. Akhirnya, dengan beberapa teman dari pulau
Seram, kami mencoba jenis ekonomi yang cocok untuk warga setempat.
Melihat keadaan alam dan kemampuan mereka bertani, kami mencoba menanam
kopi. Pada tahun 1970-an, masyarakat setempat pernah mendapat bibit kopi
dari pemerintah sebagai alternatif dari cengkeh. Ketika harga cengkeh
jatuh, mereka mulai menanam kopi. Namun, ketika harga cengkeh naik lagi,
kopi mulai ditebang. Akhirnya, kami berdialog dengan keluarga setempat,
belajar untuk memilah kopi dan semuanya dimulai dari nol.
YA:
Dalam satu kawasan perkampungan?
SP: Operasinya di seluruh pulau Seram. Teman-teman
Regu Belajar kesulitan karena transportasi yang kurang memadai.
Sehingga, mereka terbiasa membawa motor dari satu ujung ke ujung lain.
Kadang motornya dipanggul jika melewati sungai yang tidak ada
jembatannya.
YA: Jadi sekarang perkembangannya seperti apa?
SP: Itu mereka sendiri yang atur, jadi tidak ada
target. Yang penting mereka dapat memahami logika perubahan sosial
ekologis. Itulah yang kami pelajari bersama untuk mencari jalan keluar
atau proses belajar berikutnya.
HS: Mungkin saya bisa menambahkan contoh kasus lain.
Seluruh belahan utara pulau Flores sedang terancam. Pada awal tahun
1990-an sebuah penelitian dari Jepang yang menemukan bahwa wilayah
tersebut sedang mengalami desertifikasi atau penggurunan. Sejak akhir
1990an wilayah tersebut Mangan untuk dikirim ke Tiongkok dengan operasi
semut. Padahal tiga kabupaten ini, Manggarai Barat, Manggarai dan
Manggarai Timur merupakan bagian gemuk dari pulau Flores. Jadi, daerah
yang sumber airnya paling banyak,
dihajar selama bertahun-tahun. Padahal mereka terancam akan menjadi gurun juga.
Kami bolak-balik ke sana sebagai pelajar, atas undangan teman-teman
yang selalu mengabari jika ada sesuatu yang baru atau krisis baru
terjadi. Banyak yang kami temukan. Misalnya, petir di satu tanjung,
pertanda alam penting untuk awal musim tanam, tidak datang lagi ketika
tanjung dibongkar oleh pertambangan. Semua kami dokumentasikan. Sampai
saat ini desa-desa dan institusi pengurus warga utama di situ terus
berikhtiar untuk melakukan proses penyembuhan dari kehidupan warga dan
ruang-ruang hidupnya.
S
esungguhnya subyek telaah dan urusan dari arsitektur adalah ruang hidup. Akal budi kita
kan tidak mencipta, tetapi hanya menggubah.
Kembali ke pemerintah kita yang buta krisis. Karena krisisnya tidak
terkodifikasi apalagi terukur, arah perubahan sekarang justru menjadi
tawanan dari sektor pasokan. Kantor yang mana yang siap menjawab
pertanyaan mengenai duduk perkara dan bangunan krisis untuk pulau
Sulawesi atau pulau Taliabu misalnya?
Nah, sekarang kemanusiaan dan biosfera sedang dirusak cepat. Apa benar ada pemampatan waktu perubahan? Ada.
Agenda perlawanan dan pemulihan sekarang bertujuan mengembalikan
syarat keselamatan manusia dan keselamatan biosfera dalam perubahan.
Kami sebisa-bisanya menuturkan ceritanya dalam berbagai bahasa si
pelajar. Kami akan bekerja sama di lapangan bersama rekan-belajar lain
untuk mendengarkan dan mempelajari tuturan tandingan mengenai kekhasan
lintasan krisis di situ, dari warga yang paling paham tentang ruang
hidup mereka sendiri.

Saya bersama Hendro Sangkoyo, Dinar dan Sanca. ©RUANG
Catatan Kaki:
[1] Operational Landscape: Zona
untuk pengerukan sumber daya, wilayah industri agrikultur,
infrastruktur logistik dan komunikasi, turisme dan pembuangan limbah,
yang mencakup area tepi kota, daerah terpencil yang juga termasuk
“pedesaan” atau “alam terbuka”…. Hal ini merupakan bentuk pemekaran
kapitalisme yang mengandalkan pencakupan dan pengoperasian sebuah
wilayah dalam skala besar di luar kota untuk mendukung aktivitas sosial
ekonomi, siklus metabolik dan kepentingan pertumbuhan kota – (Neil
Brenners. Implosions/Explosions : Towards a Study of Planetary
Urbanization. 2014)
[2] Taylorism: Teori
manajemen yang menganalisa dan mensintesa alur produksi. Tujuan
utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi secara ekonomi, terutama
produktivitas pekerjanya. – (Wikipedia)
[3] Environmental Kuznets Curve: Hipotesa
dari sebuah hubungan antara berbagai macam indikasi dari degradasi
lingkungan dan pendapatan per kapita. Di tahap awal dari pertumbuhan
ekonomi, perusakan lingkungan dan polusi naik. Tetapi setelah pendapatan
per kapita mencapai level tertentu, tren menjadi terbalik. Peningkatan
ekonomi dalam level yang tinggi juga membawa peningkatan kualitas
lingkungan. – (David I. Stern. The Environmental Kuznets Curve. 2003)
[4] Ecological Footprint: sebuah ukuran dari dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan – (WWF)
http://membacaruang.com/hendro-sangkoyo-tentang-sde-dan-gerilya-pemulihan-krisis/